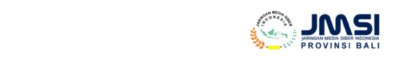Masih perlukah kita, di zaman pascamodern ini, memerlukan sosok pahlawan? Saya tidak tahu. Yang pasti pada situasi tertentu, memang kerap kita, diam-diam, merindukan kehadiran seorang yang sedikit banyak memberi kita harapan.
Saya sengaja memulai tulisan ini dengan sebuah pertanyaan, kemudian memberikan jawaban dengan nada skeptis. Barangkali, bahwa memang kita tak lagi memerlukan sosok pahlawan semisal Rambo, tokoh hero dalam film hollywood yang sanggup seorang diri terjun ke medan perang. Kita barangkali tidak mampu memahami sosok hero seperti itu. Sejarah kepahlawanan kita cenderung lebih berkarakter manusiawi. Sesosok manusia yang bisa kita sentuh. Sangat bersifat manusia.
Pahlawan sebuah predikat yang tak ringan disandang. Tak pernah merasa paling baik, paling pintar, paling benar, paling kaya apalagi paling berjasa. Rela berkorban dan menempatkan kepentingan negeri di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ruh dan semangat yang digelorakan sejak peristiwa 10 November 1945 di Surabaya adalah bagian sejarah bagi tegak dan kokohnya republik ini.
Panglima Besar Sudirman adalah satu contoh kepahlawanan kita yang sangat menyentuh itu. Tubuh yang terbalut ringkih, wajah yang lembut tapi dalam sorot mata yang tajam adalah sebuah persentuhan antara kemanusian dan sebentuk gairah yang tidak muncul dari ledakan-ledakan otot. Ia juga tidak lahir dari semacam rasa pongah yang berlebihan. Inilah yang menjadikan sejarah kepahlawanan kita lebih terasa nyaman untuk kita letakkan dalam hidup keseharian kita.
Tapi apakah kita masih memerlukan sosok pahlawan seperti ini? Apakah peradaban masih sanggup melahirkan sosok dengan kualitas dan integritas kemanusiaan seperti itu? Saya juga tidak tahu. Tapi, konon, sebuah zaman melahirkan sejarahnya sendiri. Sejarah yang terbangun dari pergulatan pikiran, rasa, kebutuhan dan jiwa zamannya. Di sekitar tahun 1970-an, bangsa ini melahirkan sosok Hoegeng. Seorang penegak hukum (pernah menjabat Kapolri) yang sangat teruji integritasnya. Ia adalah personifikasi kerinduan rakyat bagi sosok kekuasaan yang berpihak pada rakyat kecil, dan menjadi musuh besar para koruptor.
Dan kita pun tahu, sosok Hoegeng demikian ringkih dan tipis. Dia demikian gampang kita letakkan dalam ruang keseharian kita. Dia bukanlah sosok pahlawan berotot dan bermuka “coreng-moreng” semisal Rambo.
Namun, dalam konteks hari ini, alih-alih sosok pahlawan itu tumbuh subur, kultur yang muncul justru sebaliknya: kontra-produktif dengan jiwa kepahlawanan itu sendiri. Sekali lagi, setiap zaman memang hidup dengan sejarahnya sendiri, tafsir atas makna pahlawannya sendiri, juga problem kepahlawanan itu sendiri.
Kalau kita jeli, rerata orang kini mengidap apa yang disebut sindrom pahlawan atau dikenal juga dengan istilah hero complex. Kata “complex” merupakan ketidaksadaran yang berkisar pada pola memori, emosi, persepsi, dan keinginan tertentu. Sesuai penjelasan psikoanalis dari Carl Jung, hal ini terbentuk dari pengalaman dan reaksi atas pengalaman individu itu sendiri. Lebih lanjut, complex sangat dipengaruhi ketidaksadaran kolektif yang bisa diteruskan melalui keluarga, peristiwa-peristiwa khusus, atau aneka simbol dalam budaya masyarakat.
Hero complex merupakan kondisi ketika seseorang mencari pengakuan dengan cara beraksi seperti pahlawan. Ia berusaha menciptakan keadaan di mana mereka bisa menjadi juru selamat dan mendapat pujian. Tidak jarang, orang dengan hero complex melakukan hal-hal melanggar hukum dan etika sosial demi memenuhi keinginannya. Sindrom pahlawan ini menjadi sekelumit persoalan yang dihadapi generasi ini.
Pahlawan memang adalah sebuah produk dari zamannya. Sebuah zaman yang biasanya penuh dengan ketidak-pastian. Seperti ‘Zaman Edan’ yang diabadikan oleh Ki Ronggo Warsito dalam “Serat Kalitida”nya. Sebuah situasi di mana nilai-nilai moral kemanusiaan kita runtuh porak-poranda. Zaman ini kerap di tandai dengan hilangnya parameter yang sahih antara kebenaran dan kepalsuan. Kita tak lagi mengetahui siapa yang layak kita jadikan panutan dalam setiap perilaku kita. Pada situasi seperti ini, yang muncul adalah klaim kebenaran, aksi kebohongan dan jiwa pengecut.
Namun barangkali, memang setiap zaman bergerak dalam sebuah proses keseimbangan yang terus-menerus. Mungkin, ketika kita, demikian merindukan kembali sosok pahlawan, zamanpun akan menjawabnya. Inilah yang bisa kita rasakan akhir-akhir ini. Di mana kerinduan itu pelan-pelan bergulung dalam harapan dan mimpi kebanyakan rakyat kita. Di sana, kita mulai meletakkan kerinduan itu. Kita mencari sosok yang bisa meletakkan harapan dalam keseharian kita. Sosok manusia biasa, yang mampu kita sentuh namun cemerlang karena nilai-nilai kemanusian yang memayunginya. Kesederhanaan yang berintegritas. Welas kasih yang telah melampaui dirinya sendiri.
Dengan demikian, kita masih bisa berharap, di sana, dalam dimensi kemanusian yang dekat dengan keseharian kita, ada sosok pahlawan yang tidak lahir dari dorongan ingin “gagah-gagahan”, tetapi muncul sebagai bagian dari kerinduan kita akan sosok manusia yang punya integritas dan kejujuran.