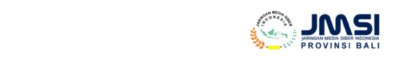Hari-hari ini, kita akrab sekali dengan percakapan soal sengketa yang tak pernah usai: tentang Israel dan Palestina. Komunikasi di ruang publik menyeruak ke dunia maya tak lepas dari diskursus tentang keduanya. Mengikuti pemberitaan keduanya (baca: Israel dan Palestina) ibarat menonton film perang yang diputar ulang. Berulang kali keduanya terlibat perseteruan dengan pola yang sama, pun dengan jumlah korban jiwa yang semakin bertambah jumlahnya.
Berakar dari kebijakan diskrimintaif, kolonialistik, dan represif Israel di Jerusalem dan sekitarnya yang diprotes dan dilawan oleh orang-orang Palestina, kemudian dijawab tindakan yang lebih brutal oleh polisi Israel, dibalas ketapel dan tembakan rudal oleh kelompok Hamas di Jalur Gaza, dan dibalas lagi dengan tindakan yang lebih beringas oleh tentara militer Israel. Begitu yang tiap kali terjadi. Selalu berulang. Perempuan, lansia, bahkan hingga balita tak pernah pilih kasih menjadi korban berikutnya.
Peristiwa itu, sebut saja “kejahatan kemanusiaan” yang dilakukan Israel terhadap Palestina memantik perhatian masyarakat global, tak terkecuali Indonesia. Protes, kecaman, hingga sumpah serapah tidak sedikit disampaikan. Mulai dari petinggi negara, kaum intelektual, aktivis kemanusiaan, mahasiswa, hingga masyarakat awam yang sebetulnya kurang paham betul inti persoalan tetap serentak seiring seirama membuka lebar-lebar pita suaranya, menyuarakan perlawanan dan mengutuk segala tindak kejahatan, baik di dunia nyata maupun melalui sosial media.
Kuatnya arus kecaman itu, membuat persoalan tampak melebar dan menjadi bias kemana-mana. Narasi-narasi mengutuk dan mengecam Israel itu seringkali dikeluarkan secara serampangan. Kecaman yang kebanyakan salah alamat. Kita jadi sulit membedakan mana bab-bab penolakan terhadap kejahatan kemanusiaan, zionis (menolak pembentukan negara Israel), hingga sikap penolakan yang cenderung antisemit (klaim kebencian dan prasangka berlebihan terhadap Yahudi sebagai rasa tau agama).
Kita semua sepakat dan tentunya ingin bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Palestina segera berakhir, dengan searif-arifnya solusi: Palestina menjadi negara yang bebas atas segala bentuk pendudukan, merdeka. Namun, alih-alih membantu mewujudkan cita-cita itu, kita justru melakukan hal yang sepertinya bertendensi menghambatnya. Bagaimana saya bisa mengatakan demikian? Mengapa sikap yang begitu mulia ini (kecaman terhadap Israel) dapat dikatakan mengahambat terwujudnya cita-cita negara Palestina merdeka? Saya jelaskan pelan-pelan agar vonis ini tidak dianggap ngalur-ngidul.
Begini, sikap antisemit/anti terhadap ras Yahudi merupakan sikap yang ditolak sebagai strategi perjuangan oleh orang-orang Palestina. Khaled Meshaal, salah seorang pemimpin tertinggi Hamas mengatakan dalam sebuah wawancara: “Kami bukan fanatik. Kami bukan fundamentalis. Kami tidak melawan Yahudi karena mereka Yahudi. Kami tidak melawan ras manapun. Kami melawan penjajah”; “Kami tidak berperang berdasarkan agama, kami memerangi penjajahan,” ujar Meshaal. Jika petinggi Hamas saja mengatakan demikian, mengapa kita justru berkempanye dengan sikap antisemit? Hal ini tentu terlihat sepele untuk tidak menyebutnya sangat “complicated”. Saya jelaskan mengapa sikap anti terhadap ras Yahudi ini bisa tidak menguntungkan Palestina. Meski kita sepakat untuk tidak berbicara dalam konteks kepercayaan, saya sampaikan bahwa secara kemanusiaan, tidak semua orang Yahudi itu jahat, sebagaimana tidak semua muslim itu baik. Ini keniscayaan dalam soal kemanusiaan. Sikap antisemit yang disuarakan untuk mengutuk kolonialisme Israel atas Palestina, bisa menjadi bumerang terhadap eksistensi Palestina di mata dunia, semacam senjata makan tuan.
Begini, zionis kolonial Israel telah memanfaatkan narasi kebencian terhadap Yahudi ini untuk menarik simpati dunia. Istilahnya playing victim. Dunia bersimpati dan mendukung Palestina merdeka karena zionisme dan kolonialisme Israel, bukan karena penduduk Israel mayoritas memiliki aliran gen dari ras dan agama Yahudi. Banyak orang Yahudi di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Israel mengafirmasi penolakan rakyat Palestina terhadap zionisme Israel. Ketika narasi antisemit ini digunakan untuk mendukung Palestina merdeka, maka kita juga dapat menyinggung perasaan orang-orang Yahudi yang turut membela Palestina. Jangan lupakan juga bahwa di Palestina, hidup dan bertempat tinggal pula eksponen Yahudi yang ikut melawan kolonialisme Israel. Mereka secara eksodus bergerak bersama umat muslim di Palestina melawan diskriminasi dan penindasan. Antisemit jelas melemahkan kekuatan Palestina secara elektoral dan global. Menggunakan argumen antisemit akan membuat pihak yang memiliki ras atau beragama Yahudi pendukung Palestina merdeka merasa ikut diserang, dan itu merugikan untuk perjuangan Palestina merdeka.
Kita juga kerap lupa bahwa Palestina adalah rumah bagi agama kristen. Di Betlehem dan Yerusalem tanah-tanah ini pernah disinggahi Yesus, kekristenan lahir di tanah ini. Maka ketika Palestina direbut dan dijajah oleh Israel, ini bukan lagi perkara satu agama, tetapi sebuah pertikaian panjang tentang identitas keimanan. Israel merasa bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan, sementara warga Palestina menganggap ini adalah tumpah darahnya. Pemuda-pemuda kristen Palestina menjelang natal kerap berpakaian seperti Santa Klaus untuk menunjukkan bahwa mereka menolak penjajahan Israel. Mereka bertikai dan bentrok dengan otoritas Israel karena dianggap tak pernah ada. Pada perayaan Natal 2015, pemuda-pemuda kristen Palestina membagikan kado di Betlehem yang direspon represif oleh pemerintah Israel. Dengan pakaian Santa Klaus mereka melempar batu dan dibantu pemuda muslim melakukan perlawanan kecil terhadap militer Israel.
Palestina juga bukan hanya rumah bagi mereka yang berafiliasi dengan agama. Kelompok komunis juga salah satu yang aktif bergerak membela dan melakukan advokasi kemerdekaan Palestina. Setidaknya ada beberapa partai dengan haluan sosialisme di Palestina dan Partai Komunis Israel secara terbuka menolak keberadaan zionisme dan penjajahan atas Palestina. Sekali lagi, ini bukan lagi soal agama, ras, maupun golongan, ini soal kemanusiaan. Sebagaimana narasi bahwa “Anda tidak perlu menjadi muslim untuk membela Palestina, Anda hanya perlu menjadi manusia”.
Saya dan barangkali kita semua, selalu ingin Palestina merdeka, dan perdamaian di atas dunia menjadi pemandangan rutin setiap harinya. Dalam konteks membela Palestina, kita mesti lebih bijak dan hati-hati. Setidaknya, jika tidak bisa membantu mewujudkan cita-cita merdeka, kita jangan melakukan hal-hal yang justru memperlebar jarak antara cita-cita itu dan realitasnya. Tidak ada lagi alasan atas nama pembelaan, kita menggunakan narasi kecaman yang makin memperuncing permasalahan. Sebab sekali lagi, dunia tidak bertanggungjawab atas ketidaktahuan kita.
Dalam rangka perjuangan terhadap kemerdekaan Palestina, kita juga mesti lebih selektif dan visioner dalam memilih bahasa (terminologi atau istilah) untuk mendefinisikan relasi keduanya (baca: Israel dan Palestina). Penggunaan kata “perang” dan “konflik” pada serangan Israel ke penduduk Palestina sejatinya menutup-tutupi apa yang terjadi. Sebab pilihan istilah ini seringkali dapat membuat kita tertipu dengan mengatakan bahwa masalah yang terjadi di perbatasan Israel-Palestina ini sebagai perang sipil atau konflik. Propaganda melalui penggunaan bahasa merupakan hal yang lazim dilakukan oleh media, tergantung pada siapa afiliasinya. Agak sedih jika kita terpedaya oleh siasat semacam ini.
Perhatikan lagi dua kata ini: ‘perang’ dan ‘konflik’. Kedua kata itu sejatinya menyiratkan bahwa kedua belah pihak itu setara, sama kuatnya, dan sama berbahayanya. Padahal jika kita mau sedikit lebih jeli, tidak ada yang setara antara militer Israel dengan warga sipil Palestina, asimetris. Apa yang terjadi di sana jelas merupakan penjajahan, pendudukan, pembantaian, dan pengusiran paksa. Ghassan Kanafai, seorang aktivis pembebasan Palestina, sejak 1970, sudah pernah secara tegas membantah penggunaan kedua istilah ini. Hal ini muncul ketika Ghassan lumayan kesal ketika seorang jurnalis mewawancarainya dengan menggunakan istilah “perang sipil” atau “konflik” pada masalah Israel dengan Palestina. “Ini bukan perang sipil! ini adalah orang-orang yang mempertahankan dirinya melawan pemerintahan fasis, yang sedang Anda bela. Ini bukan perang sipil.”; “Ini bukan sebuah konflik. Ini adalah gerakan pembebasan yang berjuang untuk keadilan,” tegas Ghassan kepada jurnalis itu.
Sejarah pertumpahan darah Israel-Palestina adalah sejarah penjajahan yang belum usai. Ia bermula dari akhir sebuah masa penjajahan negara-negara Eropa, yang digantikan oleh penjajahan satu negara ke negara lain. Penjajahan itu diwariskan dari satu entitas ke entitas lain. Rezim boleh berganti—dari pemimpin ke pemimpin Partai Buruh sampai kebangkitan kelompok imperialis garis keras pimpinan Netanyahu. Tapi, tidak ada yang berubah. Sejarah berdirinya Israel adalah juga sejarah penindasan terhadap rakyat Palestina.
Sebagai manusia, kita punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai penjajahan itu. Namun, atas nama ketidaktahuan, berhentilah bertindak seolah membela tetapi di saat yang sama, kita justru melakukan sesuatu yang berpotensi melanggengkan penindasan itu. Meski dalam perang, rekam jejak membuktikan Israel lebih sering mengangkat kepala, tapi itu tak berarti Israel tak pernah tersungkur dan kalah dipukul mundur. Pada 1973, Mesir yang kala itu dipimpin oleh Anwar Sadat, membuat satu gebrakan: membebaskan dataran tinggi Golan dan Sinai, yang tadinya dikuasai oleh Israel setelah perang 1967. Membuka satu perspektif baru: Israel tidak selamanya tak terkalahkan.
Dalam konteks penjajahan Israel atas Palestina hari ini, cita-cita kemerdekaan Palestina dan kekalahan Israel bukan menjadi hal yang mustahil terjadi. Hal ini mungkin terjadi jika perjuangan tidak pernah lepas dari gerakan-gerakan perlawan intelektual. Ajak keluarga, sahabat, dan kolega memastikan bahwa kita telah berpatisipasi untuk mengatakan “tidak” pada penjajahan atas nama apapun. Lakukan apa yang bisa dilakukan, jika tidak bisa, cukup lakukan sesuatu yang tidak juga menghambat kemerdekaan Palestina dan berpotensi melegitimasi konflik komunal yang tanpa daya apapun untuk melawan relasi-kuasa yang silang sengkarut di luar sana.
Sebagai manusia, kita juga punya doa. Selemah-lemahnya jihad adalah doa. Kita tentu tak harus berpangku tangan sembari hanya memilih menunggu sang penunggang kuda akhir zaman muncul kemudian membasmi setiap kemungkaran yang ada. (*)