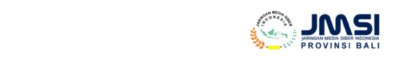Entah berapa kali aku berjumpa dengan Ramadhan. Entah berapa kali pula aku meninggalkannya. Sekian kali aku bertemu Ramadhan, sekian kali pula kuramaikan masjid dan musholla. Sekian kali pula ayat suci-MU dilantunkan dengan pengeras suara sepanjang malam.
Suasana yang menyejukkan, meneduhkan, menggetarkan hati dan menambah keimanan ….idza dzukirallah wajilat qulubuhum waiza tuliyat ‘alaihim ayaatuhu zaadathum imaana… (Qala Allah).
Tak terbayang manakala hati bergetar saat mendengar ayat Allah akan menggetarkan pula semangatku untuk tak melakukan kesalahan berikutnya pada peristiwa yang sama di sebelas bulan kemudian.
Voltase kekuatan Qur’an seolah merontokkan bintang gemintang dari tangkainya, memenuhi angkasa kampungku yang membawanya ke dalam qalbu setelah prosesi menahan diri sebulan penuh. Dengan begitu aku akan tetap menahan diri pula usai Ramadhan disetiap sepak terjang pergaulan sosialku.
Para penceramah, muballigh, khatib dan sebagainya ber fastabikul khairat mengabarkan bahwa aku diberikan kasih sayangNya, ampunanNya dan terhindar dari api nerakaNya (Rahmat, Maghfirah dan Itqun Minan Nar) pada sepuluh hari pertama, kedua dan sepuluh hari terahir, selama menikmati lapar dan dahaga, serta keinginan tak bermesraan dengan isteri disiang hari.
Beragam tema disuarakan oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Mulai dari bulan penuh ampunan, bulan introspeksi, bulan barokah, bulan kasih sayang, bulan seribu bulan, bulan melatih kepekaan sosial, serta bulan-bulan lainnya yang tak mungkin bisa diungkap di ruang terbatas ini.
Namun adakah jaminan aku sudah faham? Adakah peningkatan penghayatan dari proses permenungan selama berpuasa? Apakah gerak sosial Ramadhanku masih jalan ditempat? Adakah aku makin peduli sesama? Adakah aku masih suka saling mencaci lagi? Apakah aku tak menjadikan buruk sangka sebagai makanan siap saji disetiap obrolan dan diskusi?
Adakah di sepuluh hari terahir kejahatan dikampungku tak meningkat meski pintu neraka ditutup? Adakah ruang didalam hati dan pikiranku untuk sesekali bertanya, bahwa yang salah bukan hanya mereka, tetapi juga aku? Adakah tindakan dan ucapanku tak lagi mencederai perasan saudaraku lainnya? Adakah aku tak lagi merasa benar sendiri, yang lainnya kafir sesat dan hanya aku yang suci sehingga berhak atas syorgaNya?
Begitulah pertanyaan yang meluncur dibenakku menjawab apa yang kulihat dihadapanku sejak dimulai hingga usai Ramadahan sepanjang tahun. Ketika Ramadhan datang kuramaikan masjid dan musholla. Ketika berakhir aku tak menjadikannya landasan nilai dalam pergaulan yang lebih produktif dan bermanfaat untuk pembangunan kampungku.
Datang dan perginya Ramadhan telah kurasakan setiap tahunnya. Laksana seorang tamu yang hendak mengunjungi rumah, akupun punya cara yang beda menyambutnya.
Jika yang datang adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, aku akan sangat bangga menerimanya dengan segala persiapan yang diatur sedemikian rupa, hingga suasana penyambutan itu sudah sesuai dengan anjuran untuk ikromudldlaif – memuliakan tamu.
Namun ketika sang Ramadhan tiba, aku hanya sibuk mengirim ucapan melalui Sosmed, Spanduk, Poster dan Baliho. Kupasang fotoku yang berkopiah dengan baju putih dan kedua telapak tangan saling bersentuhan di depan dada. Kutulis ucapan selamat berpuasa dengan kalimat khusus yang tak boleh kutinggalkan yakni “Marhaban ya Ramadhan” dan kutambah dengan kalimat pemaksaan yakni “Hormati Orang Berpuasa”. Padahal siapa yang tau kalau aku berpuasa dan anehnya, aku kok butuh penghormatan dari orang yang tak puasa.
Aku juga bertadarrus di kanal sosmedku, meski bacaan Qur’anku belepotan. Tak bisa kubedakan mana huruf zal, dzal, jim dan ‘ain. Tak berseuaian makhraj dan tajwid yang meluncur dari rongga mulutku. Aku tak peduli bahwa yang menonton dan mendengar bacaanku punya hukum wajib memperbaikinya.
Di Sosmed kusajikan penampilanku laksana seorang berilmu agama yang mumpuni. Akupun tampil berceramah. Dengan modal kitab terjemahan, aku mengurai kehidupan sesuai seleraku. Tak peduli dengan metodologi keilmuan (ilmu alat) yang tak kumiliki, yang penting aku mulai beraksi di publik.
Padahal untuk membaca Qur’an harus belajar ilmu alat yang disebut Tajwid. Untuk memahaminya harus belajar ilmu alat yakni Nahwu, Shorof, Balaghah hingga Mantiq dan tentang Asbabun Nuzul sehingga faham Tafsirnya. Serta banyak lagi rumpun dan turunan ilmu alat yang dipelajari. Bukankah seorang lawyer harus sekolah di Fakultas Hukum untuk belajar metodologi hukum kemudian boleh membuka praktik pengacara?
Begitupula disaat aku diminta mengatur media. Akupun mempersiapkan strategi yang membuat semua pendengar dan pemirsa terpesona. Sebab aku sadar, media adalah ruang industri. Maka tak mungkin setiap acara tak beroleh keuntungan. Tak mungkin setiap menit tak bernilai rupiah. Bahkan jelang azan maghrib-pun menjadi waktu sangat mahal bagi produk iklan.
Lantas aku mendekati mereka yang gemar tampil dan bersuara. Kurayu mereka dengan alasan memempertahankan posisi jabatan dan suara di pemilukada nanti. Kemudian semua berbondong menjadi orang bijak saat aku mendengar radio jelang azan Maghrib dan Imsak. Ada yang mengucapkan selamat berbuka dengan gaya deklamasi seperti anak kecil yang ikut lomba di kampung.
Di televisipun demikian, aku akan cari artis yang bisa ceramah dan penceramah yang bisa jadi artis. Ini keuntungan ganda yang diraup dalam Ramadhan. Inilah berkah Ramadhan. Tuhan memang sedang berpihak denganku.
Soal puasa? Ah… ini soal sepele. Aku sudah terlatih untuk mempertontonkan caraku beragama yang dapat memukau semua orang. Toh semangat bernegara sudah merasuki semangat beragamaku. Jadi mereka pasti tau bagaimana mengemas agama dalam etalase modern seperti ini.
Dalam soal puasa, aku hanya mengubah jadwal makan minum dan istirahat saja. Ketika lapar dahaga terasa. Aku seolah sadar dan merasakan penderitaan si miskin yang melarat itu. Bagiku ini akan membuatku kelak memiliki kepekaan sosial, seperti kebanyakan pemahaman banyak orang.
Sekarang aku sudah semakin pintar. Paling tidak, semakin pintar berdalih dan bertengkar atas nama harga diri. Menipu demi perut anak istri. Merumuskan narasi baru untuk merendahkan martabat orang lain demi kebebasan bicara. Berbuat semaunya atas nama demokrasi. Tak berbuat sesuatu demi keamanan pribadi dan membiarkan kemungkaran demi perdamaian.
Biarlah hanya aku yang demikian, kalian tidak…(*)