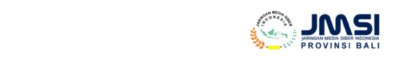Pada 1 Juni 2008, Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur pernah berujar, “….pada waktunya, saya yang akan membubarkan FPI”. Belum sempat merealisasikannya, ulama kharismatik itu lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Namun, 30 Desember 2020, tepat 12 tahun kemudian, di hari haulnya, mimpi Gus Dur terwujud. Meski bukan lewat tangannya, Front Pembela Islam (FPI) akhirnya dibubarkan oleh rezim yang berkuasa.
Akan tetapi, dalam konteks yang lebih luas, seandainya Bapak Pluralisme itu masih hidup, lelucon macam apakah yang akan ia lontarkan melihat FPI dibubarkan? atau mungkin, barangkali, ia akan sedikit mengernyitkan dahi melihat apa yang terjadi dan dilakukan terhadap FPI, entahlah.
Lepas dari itu, pemerintah memang telah resmi membubarkan FPI dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI. Pembubaran dan penghentian kegiatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. SKB yang memuat enam musabab pembubaran tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, minus Lord Luhut.
SKB itu menjadi klimaks atas rentetan kejadian yang terjadi sebelumnya. Catatan awal dapat dimulai dari kepulangan imam besar Rizieq Sihab ke tanah air. Kepulangan itu jelas menimbulkan kerumunan massa, padahal sebelumnya sempat diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh Mahfud. Dari kerumunan ke kerumunan. Di Petamburan, kediamannya, massa sudah menyemut dan menunggu kedatangan sang patron. Tiga hari setelahnya, peringatan maulid yang dihadiri Rizieq Sihab juga tidak lepas dari kerumunan massa. Imbasnya, tiga kepala daerah dipanggil dan dua kapolda dicopot. Tak pelak, nama Rizieq Sihab terseret, ia didakwa atas pelanggaran protokol kesehatan, pentolan FPI itu resmi jadi tersangka. Atas nama pagebluk, FPI akhirnya ikut digebuk.
Masih dalam satu termin kejadian, pada Kamis, 7/12/2020 terjadi tragedi kemanusiaan di rest area Tol Cikampek Km 50. Enam laskar FPI tewas di tangan aparat. Kejadian yang menghilangkan nyawa enam warga sipil itu menjadi bukti pelik bahwa kemanusiaan di negeri ini sedang dicekik. Pada Jumat 08/01/2021 rilis Komnas HAM menyebutkan bahwa penembakan laskar FPI harus diproses hukum sebab melanggar Hak Asasi Manusia.
Pembubaran FPI (yang selanjutnya akan disebut ormas) seolah mempertontonkan watak kekuasaan yang tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam prinsipnya, demokrasi merupakan salah satu dari 12 prinsip negara hukum sebagaimana diuraikan oleh Prof Jimly Asshidiqie. Ia memaparkan bahwa hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Supremasi hukum tergantung selera empunya kuasa. Benar kata Jopin, “kelewat paham memang bisa menjadikanmu hampa”.
Dalam konteks pembubaran ormas itu, yang padanya memuat tragedi kemnusiaan, menjadi teranglah apa yang dikatakan Max Weber dalam tulisannya Politic is a Vacation atau bila diterjemahkan secara kasar menjadi “Politik Sebagai Sebuah Panggilan”. Dalam esai itu, Weber bicara tentang tiga hal, salah satunya ialah soal negara. Ia merangkai definsi negara menjadi otoritas / pemegang monopoli atas penggunaan kekerasan. Di dalam negara modern tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan kekerasan di luar lembaga yang resmi yang dikendalikan oleh negara. Dalam perspektif negara Weberian, tidak akan pernah mengenal organisasi seperti PAM Swakarsa, misalnya. Apalagi milisi-milisi yang merasa berhak untuk memaksakan kehendaknya. Lepas dari sentiment politis, di sinilah barangkali ormas (FPI) dianggap telah melewati batas kewajarannya sebagai suatu ormas. Pertanyaannya, apakah Indonesia termasuk negara penganut aliran Weberian? Tentu tidak. “Demokrasi tidak – tidak,” kata tokoh kita, Amien Rais.
Kalau dicermati lagi, enam peluru yang menjadi postulat dalam SKB pembubaran ormas tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum telah pincang dan berat sebelah. Timbangan dan penimbangnya tentu sangat jauh dari kata “adil” yang menjadi akar kata “keadilan” pada sila kelima Pancasila. Pada poin inilah, kekuasaan seolah mempunyai kuasa secara subjektif untuk memberikan definisi terhadap makna keadilan itu sendiri. Dalam bingkai yang lebih luas, pembubaran ormas ini (baca: FPI) memparodikan psikologis kekuasaan yang membabi – buta demi tetap menjaga relasi dan mempeluas hegemoni kuasanya. Terdapat dua poin utama yang bisa dibaca secara kasat mata ihwal pembubaran ormas ini: delik ketidakpatuhan dan arogansi kekuasaan.
Delik Ketidakpatuhan
Terdapat paragraf menarik di awal buku Erich Fromm yang mengulas habis perihal ketidakpatuhan. “Berabad – abad lamanya para raja, imam dan pendeta, pengusaha feodal, miliarder, dan orang tua selalu menanamkan di dalam benak kita bahwa: kepatuhan adalah kebajikan yang utama dan ketidakpatuhan adalah keburukan yang nista. Namun sekarang, coba kita putar 180 derajat cara pandang ini dan pahami pernyataan berikut: sejarah umat manusia berawal dari ketidakpatuhan, dan bukan tidak mungkin sejarah umat manusia justru akan berakhir karena tindakan kepatuhan”.
Dari aspek teologis, terutama agama samawi, percaya bahwa sejarah umat manusia berawal dari tindakan ketidakpatuhan. Adam dan Hawa yang sebelumnya tinggal di Taman Firdaus, tetapi karena melanggar aturan Tuhan, mereka kemudian ditendang dari apa yang orang beriman dengan latah menyebutnya sebagai “surga”. Peristiwa inilah yang menjadi langkah awal menuju kemerdekaan dan kebebasan, menjadi janin atas lahirnya ketidakpatuhan – ketidakpatuahn berikutnya. Itulah fajar awal sejarah umat manusia.
Seperti juga Adam dan Hawa, Prothomeus dalam mitos Yunani juga menganggap semua peradaban manusia sebagai akibat dari tindakan ketidakpatuhan. Prothomeus mencuri api pengetahuan dari para dewa dan menjadikan pengetahuan itu sebagai peletak dasar evolusi manusia. Sama dengan Adam dan Hawa, Prothomeus pun dihukum. Alih – alih bertobat dan memohon ampun, dengan bangga ia kukuhkan , “lebih baik aku dirantai di batu besar ini daripada harus menjadi budak manut para dewa”.
Dari kedua cerita nenek moyang itu, kita dapat melihat apa sebetulnya hakikat daripada ‘ketidakpatuhan’ itu. Dalam arti paling jauh, pada konteks tertentu, ketidakpatuhan tidak selalu berarti buruk. Tindakan ketidakpatuhan itu membebaskan Adam dan Hawa dalam membuka cakrawala pandangan mereka, juga peradaban yang lahir setelahnya. Apa yang dilakukan Prothomeus juga membuat ia hadir sebagai juru selamat pengetahuan. Lalu setelahnya, manusia terus berevolusi dengan berbagai macam aksi ketidakpatuhan.
Namun demikian, saya juga tidak bermaksud mengatakan bahwa semua sikap dan tindakan ketidakpatuhan adalah kebajikan, dan semua sikap kepatuhan adalah keburukan. Tidak, tidak secepat itu! Cara pandang yang demikian mengabaikan hubungan dialektis antara sikap kepatuhan dan ketidakpatuhan. Kalau kita mematuhi hukum – hukum negara yang tidak manusiawi, berarti kita sudah melanggar hukum – hukum kemanusiaan. Sebaliknya, dengan mematuhi hukum negara yang manusiawi, dipastikan kita tidak akan mematuhi hukum negara yang tidak manusiawi.
Dalam konteks inilah, CCTV kekuasaan telah melihat segelintir tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan ormas hingga akhirnya dibubarkan. Pemerintah seolah berkata, “Kalian (ormas) tidak patuh dan jadi benalu kekuasaan, maka kalian harus dibubarkan”. Namun tunggu, benarkah apa yang dilakukan ormas ini bisa disebut tindakan ketidakpatuhan? Jawabannya pasti ‘iya’ jika kita menggunakan makna ketidakpatuhan dari perspektif negara. Di sini perlu diperjelas, definisi tentang “ketidakpatuhan” sangat subyektif. Tentu, otoritas yang memegang kendali atas hal itu ialah kekuasaan. Telah jelas mana tulang dan daging. Apa yang disebut ketidakpatuhan adalah jika ada orang/kelompok orang yang berani bersikap kritis dan kontra terhadap pemerintah. Ini kebijkan yang tentu kontra-produktif.
Lewat kacamata politik, motif pembubaran ini sangat mudah dibaca. Ormas (baca: FPI) berpotensi menjadi kekuatan politik besar. Ormas ini menjadi simbol kekuatan baru oposisi pemerintah. Lebih lagi jika melihat polarisasi berbasis sentimen agama semakin mengakar. Lewat kultur pemerintahan semacam ini, bukan hal yang mustahil, eksekutif dengan kuasanya akan sangat gampang mengekang kebebasan organisasi masyarakat sipil yang cenderung memiliki sikap politik bersemberangan dengan pemerintah. Dalam konteks inilah, ke depan kita kita perlu front yang lebih kuat untuk melakukan pembelaan itu di masa depan.
Dalam alam demokrasi, kritik dan perbedaan pandangan adalah instrumen di mana rakyat, secara bebas dapat berpikir (separe aude) dan ikut terlibat dalam pembangunan negara. Ini merupakan sikap pembuktian bahwa mereka yang terlibat aktif di dalamnya memiliki kesadaran untuk ikut mengawal pengelolaan umat dan negara. Ketika kritik itu hidup, penanda bahwa demokrasi kita juga hidup. Sebaliknya, ketika kritik dipersempit, apalagi dipasung, sekalipun atas nama kekuasaan dan otoritas, maka yang demikian adalah penanda bahwa ada masalah dalam demokrasi.
Kritik, perbedaan pendapat dan sikap seharusnya dinikmati, bukan malah dikebiri atau dipersekusi. Namun, apa yang tampak hari ini terlihat seperti paradoks dengan apa yang mestinya terjadi. Kekuasaan adidaya dengan kedigdayaannya menganggap yang kontra dengannya ialah penghambat hasrat kuasanya. Segala hal yang berlawanan dilawan dengan otoritarianisme dan watak arogan. Menguatlah arogansi kekuasaaan. Kepatuhan pada kekuasaan menjadi menjadi dakwah akan dogma kebajikan. Ini preseden buruk bagi demokrasi dan pemerintahan.
Dalam konteks awal, organisasi masyarakat sipil kehilangan kapasistas dan kemampuan untuk tidak patuh, karena mereka sebenarnya sudah tidak menyadari lagi bahwa selama ini mereka sudah bersikap patuh. Pada titik nadir bentang sejarah ini, kemampuan untuk meragukan, mempertanyakan, mengkritik, dan tidak patuh mungkin satu – satunya tonggak penentu antar masa depan umat manusia dan akhir peradaban.(*)