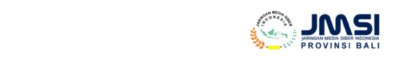Oleh : LALU MUHAMAD HELMI AKBAR
Alih fungsi status bangunan bersejarah Hagia Sophia memantik perdebatan dunia internasional. Polemik ini bermula ketika Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menandatangani dekrit yang menjadi dasar hukum perubahan status Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah yang oportunis. Lepas dari sentimen politis di balik pengalihfungsian museum Hagia Sophia menjadi masjid, terdapat kenyataan yang barangkali memedihkan tentang ‘muruah’ museum. Dalam arti lain, kita dibawa kepada pertanyaan subtil tentang: Bagaimana sejatinya eksistensi museum decade ini? Pertanyaan ini terlihat sangat sepele namun memikul cukup banyak beban. Mengapa demikian? Pertama, jika kita kontekstualisasikan pertanyaan di atas dalam kasus refungsionalisasi terhadap status museum Hagia Sophia, maka akan tampak gambaran kecil ihwal atensi yang diberikan kepada museum di era ini terindikasi sangat minim dan terkesan diabaikan.
Jika kita lihat secara lebih mendalam, premis ini akan sangat sulit dibantah. Dalam era ini, museum tampak bergerak lebih lambat jika dibandingkan dengan perkembangan zaman. Kedua, sebagai implikasi dari sebab pertama, menukil dari katadata.co.id bahwa jumlah pengunjung museum dari tahun ke tahun relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2019, tercatat hanya sekitar 2% penduduk Indonesia yang mengunjungi museum. Untuk melihat secara lebih mendalam problematika yang ada, baiknya kita melihat landasan historis terbentuknya museum.
Secara etimologi, kata museum berakar dari kata latin museion, yang bermakna kuil untuk sembilan Dewi Muse, anak-anak Dewa Zeus yang tugas utamanya adalah menghibur. Dewi Muses melambangkan ilmu dan kesenian. Seiring itu, menyadur dari buku The Greatest Philosophers dalam dekade awal kemunculannya, museum diceritakan menjadi tempat kerja ahli-ahli pikir (filsuf) zaman Yunani kuno, seperti Pythagoras dan Plato. Filsuf menggunakan museum sebagai media dalam mentarnsformasikan pikirannya. Mereka menganggap museion atau yang dikemudian hari lazim dikenal dengan nama museum menjadi tempat penyelidikan dan pendidikan filsafat, sebagai ruang lingkup ilmu dan kesenian.
Lambat laun, museum berubah menjadi tempat mengumpulkan benda-benda yang dianggap aneh. Kala itu yang disebut museum adalah tempat benda-benda pribadi milik pangeran, bangsawan, para pencipta seni dan budaya, serta para pencipta ilmu pengetahuan. Setelahnya, museum bergerak menjadi ajang prestise pribadi yang terkesan individualistik. Fenomena ini terus berlangsung dinamis di berbagai episode peradaban. Museum bercorak etnis, agama dan lembaga bermunculan. Jika berkaca dari gambaran singkat di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian museum dari zaman ke zaman selalu berubah. Hal ini disebabkan museum senantiasa mengalami perubahan tugas dan kewajibannya.
Definisi mendalam tentang museum dimuat Internasional Council of Museum (ICOM), yakni museum adalah lembaga non-profit yang bersifat permanen yang melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang bertugas untuk mengumpulkan, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan sejarah kemanusiaan yang berwujud benda dan tak-benda beserta lingkungannya, untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan hiburan. Berdasarkan intensi pada definisi museum di atas, peran yang dipikul museum menjadi sangat fundamental.
Namun, “jauh panggang dari api,” tampaknya adagium lama itu dapat dialamatkan pada konteks museum hari ini. Bagaimana tidak? Jelas kiranya bahwa misi yang diemban museum masih jauh dari predikat ‘berhasil’ dalam mencapai tujuannya. Secara epistemik, sebagaimana telah dikemukakan di muka, dalam orde ini, jumlah penambahan museum telah menunjukkan angka yang signifikan. Sebaliknya, fakta empiris mengungkapkan hasil yang memprihatinkan, oleh karena jumlah penambahan museum tidak berbanding lurus dengan angka penambahan jumlah pengunjung museum. Lebih lagi, berbicara konteks museum dari segi pengunjung, layaknya pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga,” museum mengahadapi masa yang sulit di era modern khusunya jika berbicara tentang “milenial”.
Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini (baca: milenial). Beberapa ilmuan dan pakar menggolongkannya berdasarkan tahun lahir awal dan akhir. Generasi milenial ini adalah anak-anak muda yang saat ini berusia antara 15-38 tahun. Dalam arti paling jauh, era milenial adalah era di mana seseorang mencapai periode keemasannya. Sebagai implikasi dari pesatnya perkembangan teknologi, generasi milenial memiliki karakteristik yang khas. Pola pikir, mobilitas yang tinggi merupakan hal yang membedakan generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Penggunaan teknologi digital juga turut membentuk persepsi kaum milenial dalam menalar dunia. Pemikirannya yang selalu dipacu untuk lebih maju menjadikan para milenial mengabdikan dirinya untuk pembaruan. Implikasinya, kelompok ini (baca: milenial) terlalu mendewakan kemutakhiran dan meninggalkan hal – hal yang dianggap usang.
Apa keterkaitan antara milenial dengan konteks museum di atas? Secara kuantitas, kelompok milenial ini merupakan kelompok terbesar populasi manusia abad ini. Di Indonesia, total kaum milenial pada tahun 2020 ditaksir mencapai 50% – 60% total keseluruhan penduduk. Oleh karenanya, berdasarkan realitas tersebut, eksistensi museum di era ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi kaum milenial. Oleh karenanya, museum harus memberikan perhatian lebih terhadap kaum milenial.
Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa kaum milenial mempunyai corak kehidupan yang berbeda dengan para pendahulunya.Keinginan untuk terus menciptakan pembaruan terpatri dalam diri para milenial. Kenyataan inilah yang membuat museum (yang selama ini mengandung prototipe tradisional) tidak terlalu menarik hati para milenial. Kesan tradisonal yang hinggap dalam tubuh museum ini seolah berbanding terbalik dengan apa yang menjadi nadi kaum milenial. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pandangan milenial bahwa museum terkesan inklusif.
Selain itu, salah satu alasan yang barangkali agak tendensius, dari kacamata milenial, museum tidak mencerminkan modernitas. Ditambah lagi museum masih dianggap sesuatu yang kuno, kaku, angker, dan tidak edukatif sesuai konteks zaman. Ini menjadi masalah pelik bagi museum. Akan tetapi, museum selalu berpotensi untuk menjadi sebuah gaya hidup baru di era milenial. Secara perlahan, kesadaran milenial akan urgensi museum dapat dipupuk dengan cara menyuarakan narasi bahwa pengembaraan di dalam museum dapat menjadikan milenial apapun. Dalam arti lain, museum dapat dijadikan milenial sebagai wadah dalam membaca masa depan berdasarkan perspektif masa lalu.
Harapan di atas, akan dapat diwujudkan apabila segenap pemangku kepentingan yang mengelola museum memiliki kepekaan untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengintensifkan metode quantum teaching dalam pengelolaan musuem. Menyadur dari buku Bobbi DePorter (2010: 34) Quantum Teaching bersandar pada konsep “Bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka”. Kesadaran akan frekuensi yang berbeda anatar dunia museum dengan dunia milenial akan menjadi nadi yang menggerakkan pengejawantahan prinsip ini.
Sebagai implikasi terhadap pandangan konservatif milenial tentang museum, pengimplementasian konsep quantum teaching dapat dilakukan melalui hal – hal mendasar terutama upaya redefinisi makna museum agarselalu kontekstual dengan zaman. Seperti yang telah dijelaskan di muka, makna museum dari suatu zaman ke zaman yang lain selalu mengalami perubahan. Dalam era milenial ini, makna museum juga perlu mengalami modifikasi. Kecenderungan milenial yang haus akan pengetahuan menjadikan museum harus mampu mewadahi ekspektasi tersebut. Elaine Gurian (1996) mengatakan bahwa museum harus melengkapi dirinya dengan menambah peran sebagai tempat pertemuan, di mana komunitas dapat bertemu, berdebat serta bertukar pikiran. Hal ini mesti dilakukan agar kaum milenial memandang museum sebagai rumah mengaktualisasikan dirinya.
Selain itu, dari aspek publikasi dan penyajian hasil karya, museum dapat dikemas menjadi lebih edukatif dan demokratis. Karakteristik milenial yang aktif perlu diakomodasi dalam hal interaksinya di musuem. Perubahan sikap ini akan merangsang mereka untuk juga ikut mendalami makna musuem dan aktif memberikan interpretasi terhadap apa yang dilihatnya. Seyogianya, di era milenial ini, museum tidak berhenti pada peran tradisional. Sepatutnya, mulai saat ini museum juga mengambil peran sosial dan pendidikan sehingga fungsinya juga berkembang sesuai konteksnya. (*)