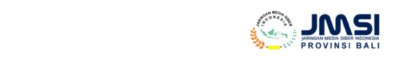Lima hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan Iskan menyempatkan diri sowan ke KH Maimoen Zubair di Rembang, Jateng.
Usianya sudah 90 tahun, tapi masih aktif mengajar. Suaranya masih lantang. Wajahnya masih segar. Dan saat mencermati kitab, beliau tidak mengenakan kacamata. Bahkan, seperti di hari Minggu kemarin, mengajarnya tiga kali.
Itulah sosok Kiai Maimoen Zubair, tokoh sentral pondok bintang sembilan Sarang, Rembang, 3 kilometer di sebelah barat perbatasan Jatim-Jateng. Saya menjadi salah satu santri dadakannya pagi itu. Terselip di antara 15-an santri tetap yang setiap minggu mengikuti jurusan mata pelajaran ini.
Kami semua menyimak kitab yang lagi dibahas. Yang tulisannya menggunakan huruf Arab gundul (tidak ada tanda bacanya). Para santri itu mengenakan sarung dan duduk bersila di lantai di hadapan kiai. Dengan sebuah kitab tua di pangkuan masing-masing. Sedangkan saya yang mengenakan sarung duduk di sofa di sebelah Kiai Maimoen mengajar. Tentu juga memangku kitab yang dimaksud.
Meski saya diminta duduk di samping kiai, bukan berarti kemampuan saya di atas para santri itu. Saya pasti kalah. Terutama dalam penguasaan Arab gundulnya. Saya memang pernah belajar ilmu nahwu shorof balaghah (tata bahasa dan sastra) selama enam tahun, tapi tidak sedalam para santri itu. Pelajaran yang saya ikuti di pondok Sarang itu adalah filsafat. Pelajaran tertinggi di pondok. Karena itu, yang mengikutinya hanya 15-an santri.
Padahal, jumlah santri di pondok Sarang ini 4 ribu orang. Filsafat, atau di situ disebut tasawuf, memang pelajaran terelite di pondok pesantren. Kian tinggi tingkat tasawuf, kian sedikit santrinya.
Dari total 140 santri yang memperdalam ilmu tasawuf, hanya 15 orang itu yang mencapai tingkat tertinggi. Karena itu, Mbah Moen –begitu panggilan akrab Kiai Maimoen Zubair– sendiri yang mengajarkannya.
Beberapa informasi melegakan juga diselipkan di sela-sela pelajaran itu. Para santri tasawuf itu, katanya, kini diakui pemerintah setingkat dengan mahasiswa S-1 jurusan filsafat. ”Berarti di sinilah jurusan filsafat yang paling banyak mahasiswanya,” ujar beliau. Mata pelajaran yang dikaji Kiai Maimoen pagi itu adalah syarah Ihya Ulumuddin. Satu pelajaran filsafat dengan pegangan kitab karya Imam Al Ghazali itu.
Kami pun masing-masing menyimak karya yang ditulis 1.000 tahun yang lalu itu. Gaya Mbah Moen mengajarkan mata pelajaran itu mengingatkan saya pada apa yang saya alami waktu masih remaja. Kiai Maimoen membaca syarah itu dalam bahasa Arab, lalu menjelaskan maksudnya dalam bahasa Jawa. Kadang dicampur Arab, Jawa, dan beberapa istilah Inggris.
Bab yang lagi dibahas adalah soal zuhud. Ajaran untuk memiliki kemampuan mengendalikan diri dari godaan-godaan duniawi. Termasuk agar bisa melawan kesenangan berhura-hura, gila harta, dan kecintaan pada yang serba kebendaan. Dalam bahasa sekarang: agar tidak mata duitan.
Tata warna, dekorasi, dan pertunjukan adalah salah satu bentuk godaan itu. Lalu tetabuhan seperti alat musik. Lalu suara merdu, bernyanyi. Lalu gerak tubuh yang kini disebut goyang. Tentu termasuk jenis goyang terbaru seperti goyang ulek-elek sampai goyang grobyak-grobyak.
Semua itu, ujar Kiai Maimoen, boleh saja. Tidak haram. Tapi, seorang tasawuf harus bisa mengendalikan dirinya untuk tidak sampai terlarut di dalamnya. Kalaupun melakukan itu, tidak boleh sampai berakibat pada timbulnya ketertarikan pada kebendaan.
Itulah pemahaman dan penangkapan saya. Kalau saya salah tangkap, kesalahan itu ada pada saya. Bukan pada kiai utama NU itu. Bukan pada kiai khos berusia 90 tahun itu. Usia 90 tahun masih aktif mengajar, masih bisa mendengar dengan sangat baik, dan masih belum berkacamata. Bicaranya masih lancar, ingatannya masih tajam (termasuk saat menceritakan perkembangan Islam sejak abad pertama), dan logika berpikirnya sangat mantik. Alangkah berkahnya. (*)