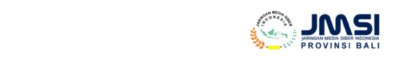Mengindonesiakan Bahasa Indonesia
Oleh: Lalu Muhamad Helmi Akbar
Aktivis LPM Pena Kampus, FKIP – Universitas Mataram
“Bahasa menunjukkan bangsa,” ungkapan itu barangkali sudah sangat familier dikenali telinga kita. Sepertinya eleborasi makna ungkapan tersebut bagi setiap individu berada di luar kepala. Akan tetapi, implementasi makna dari ungkapan tersebut sepertinya perlu kita persoalkan, dalam wujud apa ia berdiri dan dalam dimensi apa ia tak tersembunyi. Ungkapan itu membawa pesan betapa pentingnya bahasa dalam mencerminkan identitas dan jati diri suatu bangsa. Identitas suatu bangsa dapat ditunjukkan melalui bahasa. Peradaban suatu bangsa dapat dilihat melalui bahasanya. Bahasa menjelma menjadi semacam pakaian bagi suatu bangsa. Identitas suatu bangsa akan lebih mudah dikontrol melalui cara berbahasa. Bahasa yang melekat pada tubuh suatu bangsa bukan hanya sekadar simbolisasi dan lambang untuk entitas tertentu, tetapi ia membawa dimensi politis tersendiri.
Pada era keterbukaan informasi seperti saat ini, sekat – sekat yang menjadi pembatas antara satu negara dengan negara lain seringkali tidak dapat ditemukan titik koordiantanya. Titik koordinat yang dimaksud adalah wadah yang secara nyata dapat menunjukkan nilai – nilai yang lazim dikenal dan menjadi ciri suatu bangsa. Arus kemajuan ini membuat masuknya unsur budaya baru ke dalam suatu negara menjadi suatu ciri empirik yang lazim kita temukan saat ini. Bahkan, masuknya unsur luar tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mencerminkan modernitas di kalangan tertentu pada suatu bangsa. Bahasa, sebagai identitas sebuah bangsa juga menjadi salah satu objek yang terkena imbasnya. Gejala ini membuat bahasa menjadi salah satu ajang ekspansi negara – negara di dunia.
Berdasarkan fenomena semacam itu, menarik untuk membawa problematik bahasa dalam konteks keindonesiaan hari ini. Secara historis, lahirnya bahasa Indonesia pertama kali digaungkan pada kongres pemuda pertama tahun 1926. Rumusan Sumpah Pemuda pada kongres pemuda pertama ditulis oleh Muhammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Soegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kepanduan) sambil berbisik kepada Soegondo: “Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini),” katanya. Soegondo lalu membubuhi paraf pada kertas tersebut, sebagai tanda bahwa ia menyetujui usulan Muhammad Yamin. Sebelum akhirnya diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah itu lalu dibacakan oleh Soegondo, sebelum akhirnya dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Pada awalnya, rumusan singkat Yamin itu dinamakan “ikrar pemuda”, lalu diubah oleh Yamin sendiri menjadi “Sumpah Pemuda”.
Usulan Yamin pada kongres pemuda (I) butir kegita secara eksplisit menmpatkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bukan bahasa Indonesia. Hal ini mendapatkan kritik dari Tabrani Soerjowitjitro. Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu. Keputusan kongres pertama akhirnya menyatakan bahwa penetapan bahasa persatuan akan diputuskan di kongres kedua. Kritik tabrani inilah yang menjadi cikal bakal upaya konstruksi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Pendeklarasian bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 pada kongres pemuda II. Ikrar sumpah pemuda menghasilkan tiga poin kesepakatan penting yang dianggap sebagai kritalisasi semangat untuk menegaskan cita – cita berdirinya negara Indonesia. Salah satu kesepakatan yang terdapat pada butir ketiga dalam sumpah pemuda adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Keberhasilan para pemuda dalam merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan suatu langkah politis yang luar biasa visioner. Kenyataan ini, secara implisit dapat dimaknai sebagai penghilangan bentuk dominasi kelas yang bersifat mayoritas-minoritas; SARA dalam merumuskan identitas bangsa. Bagaimana tidak, mengingat kondisi perjuangan pemuda saat itu masih kental bercirikan organisasi yang bersifat kedaerahan.
Mayoritas eksponen pemuda saat itu berasal dari berbagai daerah di nusantara, terutama jong java. Penerimaan terhadap bahasa Indonesia ini seharusnya menjadi semacam teladan dalam konteks berbangsa dan bernegara hari ini. Suatu medium kebangsaan tidak boleh dikuasai oleh kelompok sosial tertentu, seperti dalam konstruksi wacana Jawa-sentris yang masih diproduksi dan didistribusikan hingga saat ini.
Bahasa Indonesia menempati posisi yang unik dalam mewujdukan nasionalisme Indonesia. Indonesia sebagai negara bekas kolonialisme justru mampu mengkonstruksi bahasanya sendiri yang berbeda dengan bahasa penjajahnya. Berbeda dengan kasus yang terjadi di negara – negara Amerika Latin yang justru menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa nasional. Dalam pada itu, dengan posisi bahasa Indonesia yang seperti itu, dapat dikatakan bahwa nasionalisme kita pertama kali adalah nasionalisme tentang bahasa.
Telah banyak bukti konkret yang menunjukkan bagaimana negara –negara di dunia membangun nasionalisme kebangsaan melalui bahasa. Israel,bangsa Yahudi yang notabene merupakan negara yang hidup di semenanjung Arab yang mayoritas beragama muslim. Sebagai negara bekas jajahan, Israel membangun peradaban awalya melalui bahasa. Demi mengukuhkan jati dirinya sebagai suatu negara, Israel membangkitkan kembali bahasa Ibrani yang telah lama mati. Hal ini dilakukan guna mengontraskan keberadaanya agar kontradiktif dengan negara – negara muslim yang mayoritas emnggunakan bahasa Arab. Israel melakukan penelitian melalui naskah – naskah kuno berbahasa Ibrani yang telah lama mati lalu kemudian mengonstruksinya menjadi bahasa Ibrani modern. Israel kemudian mengukuhkannya menjadi bahasa nasional kenegaraan.
Seiring itu, pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang secara sistem kebahasaan merupakan satu kesatuan bahasa yang bersifat egaliter. Tidak ada hierarki dalam tubuh bahasa Indonesia. Sifat bahasa semacam ini sangat identik dengan ciri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia yang homogen, berdiri di atas suku, agama dan ras yang heterogen. Sejak saat itu, bahasa Indonesia disepakati menjadi lingua franca dalam merawat kebhinekaan dan mewujudkan integrasi bangsa sebelum dan pasca-kemerdekaan.
Dalam pada itu, tentu, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat fundamental dalam pergerakan sejarah bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang menjadi warisan leluhur budaya bangsa. Jadi sudah seyogianya, bahasa Indonesia haruslah tetap dijaga dan dilestarikan sebab keberadaannya secara historis sangat vital dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bahasa mempunyai relasi makna simbolik dalam kehidupan sehari – hari. Bahasa menjadi politis selain karena bahasa merupakan medium istimewa tempat makna – makna dibentuk dan dikomunikasikan, juga merupakan alat utama yang melaluinya para pengguna membentuk pemahaman tentang diri mereka dan lingkungan sosialnya. Lalu pertanyaanya, seperti apakah citra bahasa Indonesia dalam mewujudkan nilai – nilai nasinalisme bagi penutur bahasa Indonesia? Atau bagaimana penutur bahasa Indonesia menggunakan medium bahasanya dalam konteks keindonesiaan hari ini?
Dalam konteks hari ini, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia belum menempati tempat yang bergengsi dalam hati penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seolah mencari panggung sendiri untuk menunjukkan eksistensinya. Bahasa Indonesia seperti menjadi ‘tamu’ di negerinya sendiri. Penutur bahasa Indonesia saat ini seolah kehilangan kepercayaan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kenyataan ini sungguh memedihkan, upaya marjinalisasi bahasa Indonesia justru muncul dari masyarakat tutur bahasa Indonesia itu sendiri.
Gejala menomorduakan bahasa Indonesia dan menomorsatukan bahasa asing terutama bahasa Inggris menjadi konsumsi sehari – hari. Penggunaan bahasa Inggris dianggap sebagai suatu yang mencerminkan modernitas. Pertimbangan psikologis sepertinya menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks ini. Pertimbangan psikologis itu terkait misalnya dengan status sosial, kebanggaan intelektual, ataupun asosiasi dengan peradaban yang lebih maju.
Dari perspektif sosiolinguistik, Garvin dan Mathiot (1968) telah menerangjelaskan keadaan ini dengan apa yang mereka sebut sebagai sikap bahasa. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu pada prilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Garvin dan Mathiot merumuskan tiga ciri sikap bahasa yaitu: Pertama, kesetiaan bahasa (language loyalty) yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Kedua, kebanggaan bahasa (language pride) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Ketiga, kesadaran adanya norma bahasa (awareness of the norm) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan yaitu kegiatan menggunakan bahasa (language use).
Ketiga ciri yang dikemukakan Garvin dan Mathiot tersebut merupakan ciri-ciri sikap positif terhadap bahasa. Sikap positif yaitu sikap antusiasme terhadap penggunaan bahasanya (bahasa yang digunakan oleh kelompoknya/masyarakat tutur dimana dia berada). Sebaliknya jika ciri-ciri itu sudah menghilang atau melemah dari diri seseorang atau dari diri sekelompok orang anggota masyarakat tutur, maka berarti sikap negatif terhadap suatu bahasa telah melanda diri atau kelompok orang itu. Ketiadaan gairah atau dorongan untuk mempertahankan kemandirian bahasanya merupakan salah satu penanda sikap negatif, bahwa kesetiaan bahasanya mulai melemah, yang bisa berlanjut menjadi hilang sama sekali.
Sikap negatif terhadap bahasa dapat juga terjadi bila orang atau sekelompok orang tidak mempunyai lagi rasa bangga terhadap bahasanya, dan mengalihkannya kepada bahasa lain yang bukan miliknya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: faktor politis, faktor etnis, ras, gengsi, menganggap bahasa tersebut terlalu rumit atau susah dan sebagainya. Ihwal sikap negatif terhadap bahasa inilah yang tampak menyeruak dalam penutur bahasa Indonesia. Ini tentu miris, sebab seberapa teguh masyarakat tetap menjaga, merawat, dan memakai bahasa Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh rasa bangga masyarakat terhadap kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
Krisis aktualisasi bahasa Indonesia telah merambah ke segala aspek kehidupan berbangsa dan benergara, tidak terkecuali pesta demokrasi. Pada rangkaian debat Presiden 2019, ada konstruksi wacana yang muncul ihwal usulan debat Capres – Cawapres dalam bahasa Inggris (baca: usul – usil debat pilpres berbahasa Inggris, Munginkah?). Meski masih dalam konteks wacana, tetapi hal ini sungguh menggelitik. Wacana ini ramai dibicarakan dan berseliweran di media massa. Terlepas dari kepentingan politis apa yang di bawa dalam wacana tersebut, sekali – lagi bahasa Indonesia menjadi seolah dianaktirikan oleh orang tuanya sendiri; penutur bahasa Indonesia.
Bahasa Inggris memang menjadi momok yang menakutkan bagi bahasa Indonesia hari ini. Secara epistemik bahasa Inggris telah dianggap sebagai bahasa yang mencerminkan suatu era kemajuan. Dengan label bahwa bahasa Inggis telah disepakati sebagai bahasa internasional terus dikapitalisasi. Bahasa Inggris menjadi sangat superior di atas bahasa Indonesia yang minor.
Akan tetapi, yang perlu diingat bahwa mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang secara konsisten-kolektif merupakan salah satu wujud nasionalisme kepada bangsa dan negara. Namun tentu, mengatakan bahwa masyarakat yang mempelajari bahasa Indonesia lebih nasionalis dibandingkan masyarakat yang mempelajari bahasa Inggris tentu dapat menyinggung perasaan. Tetapi sekali lagi, nasionalisme masyarakat dalam wujud aktualisasi bahasa Indoensia sejatinya perlu direkonstruksi. Hal ini penting guna menunjukkan jati diri bangsa Indonesia melalui bahasanya. Disadari maupun tidak, jika upaya marjinalisasi bahasa Indonesia terus terjadi, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia hanya tinggal cerita yang tidak lagi bermakna.
Selain itu, ancaman terkait legitimasi bahasa Indonesia yang juga terus muncul dari bahasa Melayu. Malaysia, selaku penutur resmi bahasa Melayu terus melakukan propaganda diplomatis guna mewujudkan kepentingan politisnya. Upaya internalisasi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Melayu secara sadar maupun tidak sadar masih berupaya dilakukan. Sebagai premis, tentu diperlukan upaya preventif guna menolak hal itu dengan cara paling sederhana, menumbuhkan keimanan tentang pentingnya bahasa dan berbahasa Indonesia secara konsisten.
Dari aspek yuridis, upaya menaikkan derajat bahasa Indonesia tampaknya telah mulai digalakkan, salah satunya melalui Perpres 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres ini secara subtansial berisi penguatan atas legitimasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Secara ekplisit, pengejawantahan perpres ini memuat penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden, wakil presiden dan pejabat negara yang lain baik dalam forum kenegaraan dalam negeri maupun luar negeri, komunikasi di instansi pemerintah hingga perjanjian internasional dan lain – lain.
Dikeluarkannya Perpres ini dapat kita maknai sebagai bukti kemerosotan bahasa Indonesia. Itikad baik dari pemerintah patut diapresiasi. Adanya peraturan hitam di atas putih yang mengatur tentang urgensi bahasa Indonesia berbahasa tentu sangat realistis. Akan tetapi, kecacatan perpres ini terlihat pada tidak adanya implikasi hukum yang menyertainya. Seyogianya, implikasi hukum dalam perumusan Perpres 63 tahun 2019 dapat pula dipertimbangkan, guna mempertegas esensi dari salah satu simbol negara ini. Mirisnya, setahun berlalu sejak dikeluarkannya perpres ini, tidak ada perubahan signifikan dalam dalam norma berbahasa di negara kita.
Eksistensi Bahasa dalam Konteks Budaya
Perubahan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali bahasa dan budaya dalam konteks berbangsa dan bernegara tampaknya dimulai pasca-reformasi. Mulai dari titik ini, degradasi kualitas dan kultur budaya yang di dalamnya inheren bahasa juga tidak dapat terelakkan. Dengan basis argumentasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dalam garis modernisasi, segala bentuk perubahan dianggap sebagai sebuah kemajuan.
Bahasa merupakan produk budaya. Di atas, Segelintir persoalan kebahasaan yang telah dipaparkan di atas tentu mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai produk budaya. Tanpa kesadaran kolektif terhadap aspek emotif bahasa Indonesia, bukan tidak mungkin bahasa Indonesia akan terus mengalami kemerosostan. Tidakkah kemunduran nilai rasa bahasa Indonesia pada benak penutur adalah harga yang terlalu mahal untuk setiap hal yang kita namai sebagai sebuah kemajuan?
Sepatutnya, langkah nyata guna menaikkan kembali derajat bahasa Indonesia harus mulai diberdayakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah dengan membangun kembali keimanan masyarakat Indonesia terkait pentingnya bahasa Indonesia. Agenda ini dapat dimulai dari ranah pendidikan, baik pada tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan akademis paling puncak: perguruan tinggi. Bahasa Indonesia jangan hanya dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi lebih jauh dari itu, bahasa Indonesia memiliki muatan filosofis-historis dalam mewujudkan NKRI. Diperlukan sebuah cara berbahasa yang secara kolektif dapat menguatkan ikatan batin antar setiap warga negara dalam garis komando bahasa Indonesia.
Sejarah membuktikan, ihwal paling purba dari munculnya setiap permasalahan berbangsa dan bernegara adalah hilangnya nilai rasa kesatuan terhadap budaya terutama bahasa. Sudah depatutnya, bahasa degaradasi bahasa Indonesia menjadi perhatian kita bersama. Hal ini penting guna memupuk kembali nilai rasa cinta tanah air yang diaplikasikan melalui penggunaan bahasa.Mencintai bahasa, tidak cukup hanya diimani dalam dada, tetapi butuh disuarakan, agar dunia tahu bahwa kapal besar yang kita sebut Indonesia ini tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga budaya dalam wujud bahasa, bahasa Indonesia. Sebab sekali lagi, jika tidak dijaga, menghancurkan suatu bangsa, dapat diawali dengan mengahancurkan bahasanya.(*)