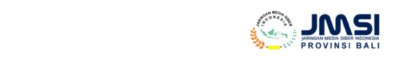Konon, di negeri antah-berantah, di suatu negeri yang katanya sangat pancasilais. Pernah terjadi dalam suatu momen keberangkatan jemaah haji, kementerian kebingungan mencari warna yang pas sebagai seragam jamaah haji. Kebingungan ini tentu bukan karena pilihan warna yang sangat sedikit, melainkan kesukaran mencari warna yang tidak berafiliasi dengan warna khas partai politik tertentu. Ini lucu dan cenderung menggelitik, di negeri itu, identitas warna saja seolah – olah telah dikaveling. Warna tampak kehilangan sifat netral dan bebas nilainya.
Di negeri nun jauh itu, pasca-gejolak yang mereka sebut sebagai masa ‘reformasi’ nyaris tak ada kemajuan berarti yang ditapaki hingga kini, 21 tahun. Saya ulangi, 21 tahun, ini tentu bukan angka yang terbilang sedikit bagi suatu negeri yang pada daratannya, tongkat kayu dan batu saja bisa jadi tanaman. Sekali lagi, 21 tahun yang kering. Itu usia di mana Muhammad Al-Fatih meruntuhkan kejayaan tembok Konstantinopel. 21 tahun juga barangkali jadi waktu yang terbilang seksi bagi Enny Arrow untuk melahirkan kumpulan karya sastra adiluhungnya. Seandainya penyair Sapardi masih hidup, mungkin ia akan menulis: “tak ada yang lebih tabah dari rakyat di negeri itu”.
Dalam rentang waktu itu, seperti tak ada yang lebih tumbuh subur pada iklim masyarakatnya selain ‘fanatisme sempit’. Ya, suatu fenomena yang telah masuk dan mewarnai kehidupan sosial masyarakatnya. Ia masuk ke dalam sendi – sendi kultus beragama, dunia politik, praktek ekonomi, olahraga, bahkan kesukuan. Ini bukan klaim serampangan yang tidak punya basis argumentasi. Gambaran kecilnya bisa dilihat dari apa yang telah disampaikan di muka. Di negeri itu, kita tak lagi leluasa dalam memilih warna.
Fanatisme sempit secara sederhana dapat dimaknai sebagai pandangan atau keyakinan berlebihan terhadap suatu aliran pemikiran baik individu maupun kelompok. Menurut Syafrudin (2012) setidaknya ada empat hal yang membuat fanatisme ini hinggap pada tubuh seseorang, yaitu: a) adanya keyakinan bahwa ideologinya adalah satu-satunya kebenaran yang harus dibelanya; b) adanya keyakinan bahwa ideologinya adalah berbeda dari ideologi-ideologi lainnya; c) adanya keyakinan bahwa ideologi yang dianutnya mampu mengantarkan kebahagiaan dunia-akhirat; d) adanya ketidaktahuan, yakni fanatik yang dasarnya hanya ikatan emosi dan atau primordial belaka, sikap ini sering disebut dengan fanatik buta.
Mari kita bedah tesis ini satu – persatu. Tesis pertama, kita akan menemukan relevansi antara fanatisme dengan menguatnya klaim kebenaran akan diri atau kelompok yang dianut. Keyakinan yang terlalu berlibahan itu (membabi buta) membuat seseorang berpikir bahwa kebenaran adalah milik atau hanya ada dalam diri atau kelompok aliran pemikiran yang dianutnya. Pandangan ini cenderung mengkultuskan kebenaran akan diri dan memutlakkan kesalahan pada orang lain. Pandangan ini sangat chauvinistik. Ini miris.
Mengapa? Sebab aliran, sebagai produk dari pemikiran, lebih lagi pemikiran personal, terlalu sempit untuk dijadikan dasar untuk memberi nilai kebenaran. Pertanyaannya, sebagai produk dari pemikiran, apakah kepercayaan terhadap suatu aliran pemikiran dapat memberikan seseorang mengklaim kebenaran? Tentu tidak. Namun, apa yang tampak hari ini adalah individu maupun kelompok menjelma menjadi otoritas yang dapat memberikan klaim terhadap kebenaran. Saya teringat ujaran budayawan Seno Gumira Ajidarma bahwa “kata kebenaran lebih baik tidak digunakan, dihindari, atau digunakan dengan hati – hati, karena kebenaran, meskipun ada, tidak bisa dikatahui”. Sekali lagi, kita mesti mafhum, keyakinan dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda.
Lalu tesis kedua. Tesis ini tentu amat sederhana dan tidak memuat beban filosofis yang terlampau berat. Dalam sejarah intelektual, kecenderungan untuk beranggapan bahwa diri atau kelompok berbeda dengan yang lain merupakan dasar kuat tumbuhnya dialektika pemikiran. Dalam ilmu psikologi, hal ini lazim disebut sebagai self efficacy dan efikasi diri. Namun, ini musti tetap dikontrol agar tidak muncul arogansi yang kemudian berimplikasi terhadap menguatnya tesis pertama tadi. Sebab, berbeda itu penting, bukan yang penting beda.
Tesis ketiga merupakan bagian tak terelakkan dari sentimen teologis. Fanatisme muncul karena kepercayaan bahwa aliran yang dianut mampu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Doktrin – doktrin keagamaan yang menjanjikan kebahagaian dengan prinsip bahwa ketaatan merupakan suatu kebajikan dan pembangkangan adalah suatu keburukan. Apakah ini buruk? Dalam arti tertentu, “tentu tidak”. Namun, pernahkan Anda mendengar frasa “fanatisme bergama?” jika doktrin di atas tidak kita anggap buruk, bagaimana hal ini bisa muncul, menyeruak ke permukaan dan bahkan dijadikan sebagai peluru tajam terhadap kelompok keagamaan tertentu?
Dalam imaji yang lebih menjengkelkan, penyematan “fanatisme” pada “fanatisme beragama” berada dalam konjungtur semacam ini, yang kerap menimbulkan tanda tanya. Mengapa “agama” menjadi basis klise dari diskursus filosofis seputar fanatisme? Ada apa dengan “agama”? Bagaimana berbicara tentang “fanatisme beragama” secara tepat, tanpa mendiskreditkan “agama” atau mencederai “kesucian” agama?
Membicarakan ihwal fanatisme beragama, kita harus mendayung di antara berbagai ekstremitas dan jebakan ideologis. Sebab kita musti hati – hati. Alih – alih memberikan kritik terhadap fanatisme beragama, kita justru akan terperangkap pada fanatisme jenis lain. Sebut saja di sini dikotomi antara “fanatisme syariah” Vis-à-vis “fanatisme konvensional”. Kalau demikin, tentu ini merupakan suatu upaya yang kontra-produktif dan mengabaikan nilai – nilai pluralisme.
Pertanyaannya, apakah dalam beragama seseorang tidak boleh bersikap fanatik? Atau kapan sebetulnya seseorang dikatakan menganut mazhab fanatisme beragama itu? Kembali kepada konsep awal bahwa fanatisme secara sederhana dimaknai sebagai sesuatu yang berlebih – lebihan. Dalam beragama, sikap semacam itu akan menggiring kepada upaya melegitimasi tesis pertama: mengkultuskan kebenaran diri dan menafikan yang lain. Tidak bijak ketika kelompok yang menganut prinsip keberagamaan tertentu, mendiskreditkan kelompok yang mempercayai prinsip keberagaman yang lain. Bukankah yang berlebih – lebihan itu tidak baik, akhi wa ukhti?
Tesis terakhir dan yang paling menggelitik. Fanatisme ini muncul tanpa dasar yang jelas, embrionya ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah ihwal paling purba dari munculnya setiap permasalahan. Fanatisme yang muasalnya adalah ketidaktahuan hanya mengedepankan aspek emosi akan melahirkan penilaian yang parsial terhadap setiap pemasalahan yang muncul. Seringkali, hal ini menjadi benih terhadap munculnya permasalahan yang lain.
Fanatisme sempit itu destruktif. Ketika fanatisme hinggap dalam tubuh seseorang, dalam fase yang ekstrem, maka ia berani mati untuk membela fanatismenya. Lihat saja, berapa banyak orang yang rela mati atas nama agama. Pun dunia olahraga, kecintaan pada idola maupun klub kebanggan, apapun akan dilakukan, sekalipun harus berujung kematian. Fanatisme membuat seseorang kehilangan akal dan bertindak irasional. Belum lagi kalau kita berbicara soal fanatisme dalam dunia politik, benang kusut akan tampak lebih runyam. Pada titik nadirnya, fanatisme melahirkan kebencian, dendam, konflik, dan permusuhan. Jika ini tidak disikap secara arif, tentu kita akan mengalami kekecewaan dan dampaknya akan lebih buruk bagi masa depan.(*)