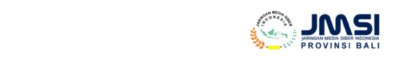Imajinasi politik seperti apa yang kita bayangkan ketika mendengar narasi bahwa politik adalah ibadah? Perdebatan panjang dan catatan kelam di masa lalu ketika konflik politik gagal ditransformasikan oleh para aktor politiknya ke dalam sebuah mekanisme institusionalisasi telah memberikan pembelajaran berharga bagi bangsa ini. Dalam pada itu, pertanyaan retoris di atas membawa kita pada suatu kenyataan subtil tentang bagaimana seyogianya hubungan antara agama – yang di dalamnya mengandung asosiasi makna “ibadah” – dengan politik. Dalam arti lain, bisakah kedua hal ini (baca: agama dan politik) disegmentasikan sebagai kesatuan aktivitas sosial kemanusiaan?
Kajian dan diskursus seputar agama (wabil khusus islam) dan politik bukanlah barang baru. Ahli pikir klasik islam telah coba membuka kotak pandora dan menyingkap tabir gelap yang ada. Di lain sisi, jerih payah para pemikir kontemporer di bawah panji “islam moderat” telah berupaya menarik benang merah keduanya. Dalam arti lain, pembahasan tentang hubungan keduanya (baca: politik dan agama) telah hidup melewati sejarah panjang dan dramatis yang dihadapi umat islam. Hasil dari perjuangan itu telah mewarnai setiap praksis kehidupan politik umat islam hingga kini. Namun tampaknya buah pemikiran dari upaya progresif itu masih belum mampu menjadi katalis yang secara kompleks dapat diterima dalam sekte kehidupan umat islam yang sakral.
Proses dialektika panjang tentang hubungan keduanya telah menghasilkan dua perspektif yang kontradiktif. Pertama, pandangan ini meyakini bahwa agama dan politik merupakan satu batang tubuh yang tak dapat dipandang secara paradoks. Implikasinya, bagi sekelompok orang, memisahkan agama dan politik adalah wacana yang tidak nyaman didengar. Bagi mereka, agama itu selalu identik dengan moralitas. Maka memisahkan agama dan politik dapat dianggap identik dengan politik tanpa moral. Dalam arti lain, menjauhkan politik dari nilai-nilai agama merupakan langkah yang kontra-produktif.
Sebagai antitesis dari argumen pertama, pandangan kedua menganggap bahwa merupakan suatu kemustahilan jika agama disetubuhkan dengan politik. Pandangan ini berporos pada argumen kontemporer, belief is one thing, and politic is another (kepercayaan atau keimanan adalah satu hal, sedangkan politik adalah hal yag lain). Logikanya, meski politisi tahu tentang prinsip – prinsip akhlak politik, namun mereka tidak mampu mengimplementasikannya dalam setiap tindakan politiknya. Dinamika pemikiran itu berimplikasi pada menguatnya polarisasi dan dikotomi terhadap cara pandang umat islam terhadap politik.
Seiring itu, akan selalu ada konsekuensi logis yang menyertai setiap pilihan terhadap kedua pandangan tersebut. Dalam sekup yang lebih kecil, doktrin agama (khususnya agama Islam) tidak dapat dilepaskan dari kungkungan realitas itu. Mengapa demikian? Pertama, bagi umat islam (barangkali juga umat beragama lain) kepatuhan terhadap Tuhan merupakan suatu keniscayaan, tetapi pada saat yang sama, mereka dihadapkan pada persoalan berikut: upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab realitas umat.
Kedua, sebagai konskuensi dari yang pertama, umat islam selalu dihadapkan pada tarik menarik antara dua kutub ekstrem berupa wahyu yang tidak pernah berubah (statis) dan realitas sosial yang cenderung berubah (dinamis). Dalam konteks ini, sejarah menunjukkan bahwa umat islam selalu berusaha memahami inti pesan wahyu Tuhan dalam rangka menjawab persoalan umat yang cenderung berubah, termasuk ihwal politik. Pada posisi ini, politik sebagai sarana ibadah memperoleh pembenaran dari dogma agama.
Selain itu, berpedoman pada akar hidup penciptaan manusia bahwa semata – mata hidup dan kehidupan ialah hanya untuk beribadah. Artinya, segala tindak – tanduk kehidupan manusia, selalu berpretensi menjadi sarana ibadah. Anggapan ini menjadi semacam postulat bahwa politik juga selalu berpotensi sebagai perwujudan praksis ibadah. Seiring itu, sebagai contoh, M. Firdaus dalam bukunya Sosiologi Politik Islam telah memberikan pandangan komprehensif terkait fokus perhatiannya terhadap jalan panjang dakwah Muhammad SAW yang ia sebut mengandung unsur manifestasi politik. Manifestasi politik dimaknai Firdaus sebagai apa yang di satu sisi berperan dalam membentuk imajinasi sosial politik kelompok muslim dan di sisi lain terkait respon musuh dakwah Rasulullah pada saat itu.
Dalam bukunya, Firdaus secara eksplisit menyebutkan bahwa dakwah Rasulullah sejak awal mengandung misi politik tertentu. Ia menambahkan bahwa telah banyak riwayat yang menujukkan bahwa dakwah Muhammad mempunyai proyek politik yang jelas dan selalu menyertainya sejak awal, tetap terjaga dan dakwah tersebut bekerja karenanya hingga ia berhasil mewujudkannya. Akan tetapi, Firdaus juga menekankan bahwa membaca dakwah Muhammad dari aspek politis tidak boleh dilepaskan dari cara pandang rival dakwah Muhammad yang sejak awal telah membacanya dengan pembacaan politik. Bagaimanapun, ilustrasi yang disampaikan Firdaus sebetulnya akan sangat bergantung pada definsi politik ia pakai dalam membedah itu.
Definisi politik sebetulnya sangat heterogen. Coraknya tergantung pada konteks dan asosiasi penggunaanya. Secara etimologi, politik berarti melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam arti ini tentu wajib relevan dengan apa yang dibenarkan syariat. Definisi ini bertolak belakang dengan paradigma politik kaum Machiavellian, end justify the means. Machiavelli menawarkan suatu metode berpikir tentang bagaimana memeperoleh dan mempertahankan kekuasaan, apapun dan bagaimanapun caranya. Lepas dari itu, tampaknya poltik memang telah mengalami perluasan makna, atau yang dalam ilmu linguistik disebut generalisasi. Politik hari ini dapat dimaknai sebagai suatu cara atau alat mendapatkan kekuasaan tanpa memperhatikan apakah cara yang digunakan dibenarkan secara syariat ataupun tidak. Definisi politik semacam ini makin menyeruak dan tidak lagi relevan dengan makna politik dalam konteks teologis.
Di sisi lain, makna ibadah telah secara gamblang menempati ruang yang luhur serta sakral dalam benak umat beragama. Ibadah dalam arti sempit merupakan representasi ketaatan. Ibadah dalam arti yang lebih luas diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa bakti dan taat kepada Tuhan: menjalankan perintahnya, serta menjauhi larangannya. Dalam pada itu, filsafat ibadah adalah teori atau analisis logis tentang prinsip – prinsip yang mendasari perbuatan yang dilakukan berdasarkan rasa bakti dan taat kepada Tuhan. Artinya, terminologi ibadah secara kultus tidaklah mengehendaki keberadaan yang batil dalam proses pelaksanaanya. Dalam konteks inilah istilah politik dan ibadah tampak tidak relevan.
Dalam pada itu, upaya membangun narasi bahwa politik adalah ibadah merupakan konsepsi yang tidak logis. Sebab secara leksikal maupun gramatikal, kedua istilah ini bertentangan, contradictio in terminis. Respon problematis ini muncul sebagai upaya diplomatis dalam menjaga segala aktivitas yang dapat dimonopoli oleh kepentingan politis. Narasi “politik adalah ibadah” yang terus dikampanyekan merupakan upaya negara atau politisi memperbarui konsepsi tentang poltik yang sesungguhnya hanyalah pemeo terkini dalam kuasa politik mempertahankan hegemoninya melalui agama.
Politik hari ini tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi ialah entitas yang memperalat segala hal guna mencapai tujuan politisnya. Narasi politik adalah ibadah tampaknya muncul sebagai kontra-hegemoni terhadap pandangan narasi politik konservatif yang melegitimasi penguasa sebagai subyek yang superior atas rakyat yang inferior. Selain itu, upaya ini juga dilakukan politisi untuk mencari suaka terhadap aspek makna dalam terminologi ibadah. Sesat pikir ini mesti disikapi secara bijak. Oleh karenanya, segala upaya yang kemudian berusaha melegalkan praktik politik yang tak senonoh harus digagalkan. Upaya politik memonopoli terminologi agama sebagai nilai tambah dalam mencapai tujuan politisnya tidak boleh dianggap remeh. Sebab jika tidak, politik akan selalu berpotensi merusak sendi kerukunan integrasi bangsa.
Kejenuhan atas realitas semacam ini dapat menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Mengapa hal ini harus menjadi perhatian kita? Indonesia pernah mengalami sejumlah peristiwa di mana kontradiksi geopolitik berimplikasi pada krisis (politik) dalam negeri yang menimbulkan korban, drama, dan trauma. Tentunya kita semua tak ingin konflik politik yang merugikan kita sebagai bangsa terulang kembali.(*)